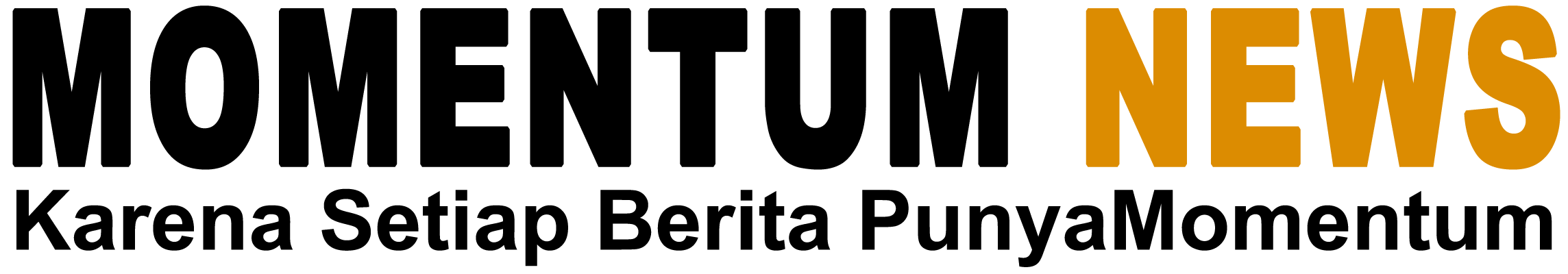Momentum News – Dalam diskursus filosofi hukum, keadilan sejatinya bukan sekadar soal legalitas prosedural, melainkan tentang moralitas dan hati nurani. Namun, realitas di lapangan kerap menampilkan wajah peradilan yang dingin, kaku, dan seolah tidak berjiwa. Kita menyaksikan sebuah paradoks besar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia: banyaknya putusan pengadilan yang pada akhirnya harus “dianulir” atau dikoreksi oleh kekuasaan eksekutif melalui mekanisme rehabilitasi, abolisi, atau amnesti.
Fenomena ini bukan sekadar statistik, melainkan alarm keras bahwa pengadilan kita sedang mengalami krisis moral. Ketika Presiden harus turun tangan memulihkan nama baik atau menghentikan proses hukum demi rasa keadilan, itu adalah bukti tak terbantahkan bahwa benteng terakhir keadilan—yaitu pengadilan—telah gagal menjalankan fungsinya.
Landasan Ideal vs Realitas Lapangan
Secara normatif, instrumen hukum kita sudah sangat lengkap. Konstitusi melalui Pasal 24 UUD 1945 menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kita memiliki UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Kejaksaan, UU Kepolisian, hingga UU Advokat yang semuanya dirancang untuk menegakkan keadilan.
Namun, keberadaan aturan-aturan tersebut seolah lumpuh ketika berhadapan dengan mentalitas penegak hukum yang “sakit”. Fakta bahwa Presiden masih perlu menggunakan hak prerogatifnya (sesuai UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan) untuk memberikan amnesti (pengampunan tindak pidana politik), abolisi (penghapusan proses hukum), dan rehabilitasi, menunjukkan adanya kecacatan fatal dalam proses peradilan.
Implikasinya jelas: jika amnesti atau abolisi diberikan, berarti ada indikasi kuat terjadinya kesalahan atau ketidakadilan dalam proses hukum sebelumnya yang melibatkan mata rantai Catur Wangsa penegak hukum: Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat.
Runtuhnya Moralitas dalam Proses Hukum
Mari kita bedah secara kritis di mana letak “ketiadaan hati” tersebut dalam setiap tahapan proses peradilan:
1. Penyelidikan dan Penyidikan yang Menindas
Di tingkat kepolisian, asas presumption of innocence (praduga tak bersalah) sering kali mati suri. Penetapan tersangka kerap dilakukan secara terburu-buru, minim bukti permulaan yang cukup, dan menabrak rambu-rambu Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014. Tidak jarang, proses ini diwarnai arogansi kekuasaan ketimbang pencarian kebenaran materiil.
2. Penuntutan yang “Bermata Dua”
Di meja penuntutan, kita sering melihat Jaksa mengajukan tuntutan ekstrem yang tidak selaras dengan fakta persidangan. Tuntutan hukum kerap kali terasa transaksional. Ada indikasi “main mata” dengan kepentingan tertentu, di mana hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Jaksa yang seharusnya menjadi dominus litis (pengendali perkara) demi keadilan, justru terjebak dalam target-target formalitas semata.
3. Hakim: “Corong Undang-Undang” yang Tuli
Inilah puncak kekecewaan publik. Hakim sering kali mengabaikan bukti-bukti yang meringankan terdakwa. Fenomena putusan copy-paste dari surat dakwaan jaksa bukan lagi rahasia umum. Pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang seharusnya menggali nilai-nilai keadilan substantif di masyarakat, justru terjebak pada positivisme hukum yang kaku. Palu hakim diketuk tanpa getaran hati nurani.
4. Advokat yang Kehilangan Integritas
Profesi yang disebut officium nobile (profesi mulia) ini pun tidak luput dari kritik. Tidak sedikit advokat yang gagal menjadi pembela sejati, malah bertindak sebagai “makelar kasus” atau perpanjangan tangan oknum penegak hukum lainnya, mengorbankan kepentingan klien demi keuntungan pribadi.
Krisis Integritas dan Matinya Hati Nurani
Masalah ini diperparah dengan fakta banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim dan panitera karena kasus suap dan gratifikasi. Ini menunjukkan masalah integritas yang sistemik. Pengadilan yang seharusnya menjadi rumah yang suci bagi para pencari keadilan, telah ternoda oleh praktik jual-beli perkara.
Pengadilan kita menampilkan wajah legal-formalistik yang angkuh, tanpa empati terhadap nasib terdakwa, terutama rakyat kecil. Padahal, semangat hukum modern telah bergeser ke arah Keadilan Restoratif (Restorative Justice) sebagaimana diamanatkan UU SPPA, dan prinsip equality before the law. Namun, di tangan penegak hukum yang tidak bermoral, prinsip-prinsip ini hanya menjadi slogan kosong.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Jika amnesti dan abolisi menjadi instrumen rutin untuk mengoreksi putusan pengadilan, maka kita harus berani menyimpulkan bahwa sistem peradilan kita tidak hanya cacat prosedural, tetapi juga cacat moral.
Negara hukum tidak akan pernah tegak hanya dengan tumpukan undang-undang, tanpa ditopang oleh penegak hukum yang bermoral. Oleh karena itu, reformasi total sistem rekrutmen dan pengawasan adalah harga mati. Kita mendesak penguatan Komisi Etik Independen yang “bertaring” untuk mengawasi perilaku hakim, jaksa, dan polisi. Selain itu, pelatihan hukum tidak boleh lagi hanya berkutat pada pasal-pasal, tetapi harus menyentuh aspek moral building dan empati.
Hukum tanpa moral adalah kezaliman. Keadilan tanpa hati nurani adalah kekerasan terselubung. Saatnya kita mengembalikan “hati” ke dalam tubuh pengadilan Indonesia.
Oleh: Ch Harno
(Ketua YLBH SAMIN SAMI AJI)