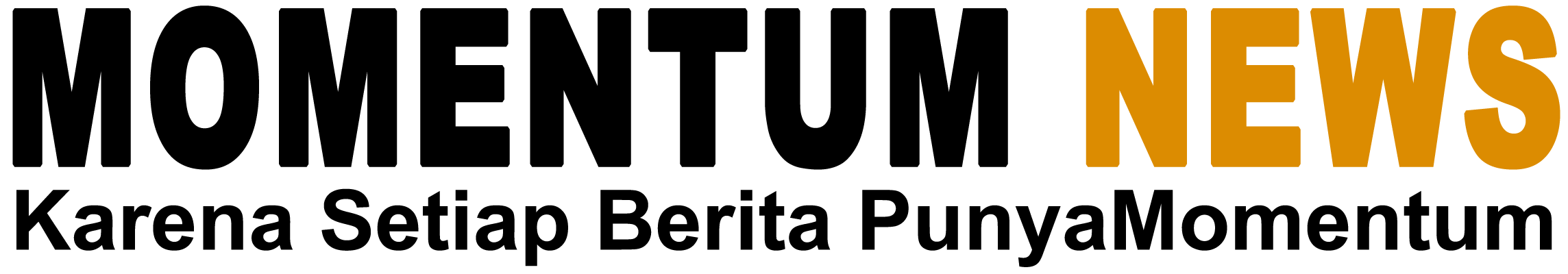Momentum News – Dalam sistem hukum Indonesia, kekuasaan Presiden untuk memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasiyang dijamin oleh Pasal 14 UUD 1945 sesungguhnya dirancang sebagai katup pengaman (safety valve). Instrumen ini berfungsi sebagai koreksi ultima ratio ketika sistem peradilan melakukan kekeliruan, baik dalam prosedur maupun penerapan hukum. Secara normatif, ia adalah alat untuk mengembalikan nama baik korban salah tangkap atau salah vonis.
Namun, praktik beberapa tahun terakhir, terutama dengan mencuatnya kasus-kasus pengampunan yang melibatkan pejabat atau elite politik, telah mengubah fungsi mulia ini menjadi ancaman tersembunyi yang merusak kepercayaan publik dan menggerogoti integritas sistem peradilan itu sendiri.
Analisis Komparatif: Dua Wajah Kekuasaan Pengampunan
Jika kita membandingkan kasus Amnesti/Abolisi era Sukarno pada 1950-an (untuk rekonsiliasi pasca-pemberontakan politik) dengan kasus-kasus kontemporer seperti rehabilitasi pejabat BUMN yang divonis korupsi atau pengampunan (Amnesti/Abolisi/Grasi) terhadap politisi elite pada tahun 2025, kita akan menemukan pergeseran fundamental.
-
Dulu (Era Konflik): Instrumen ini digunakan sebagai alat rekonsiliasi politik dan persatuan bangsa pasca-konflik besar. Meskipun sarat politik, tujuannya adalah reintegrasi sosial-politik skala besar.
-
Kini (Era Normal): Instrumen ini disalahgunakan pasca-putusan hukum yang berkekuatan tetap (inkracht), terutama melibatkan kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ini menciptakan kesan kuat adanya intervensi politik yang bertujuan menyelamatkan elite dari konsekuensi hukum.
Kasus-kasus seperti rehabilitasi bagi pejabat yang sudah divonis korupsi, atau pengampunan cepat bagi politisi tertentu, secara telanjang memperlihatkan bagaimana kekuasaan eksekutif membatalkan kerja yudikatif.
Dampak Serius: Erosi Kepercayaan dan Independensi Yudisial
Penggunaan hak prerogatif Presiden yang bersifat diskresional, khususnya pada kasus-kasus sensitif elite, membawa tiga risiko serius:
1. Melemahnya Independensi Peradilan
Prinsip Trias Politica dan checks-and-balances mengharuskan kekuasaan kehakiman harus bebas dari intervensi kekuasaan lain. Ketika keputusan vonis yang sudah melalui proses panjang di pengadilan, Mahkamah Agung (MA), atau bahkan Peninjauan Kembali (PK) bisa dibatalkan oleh satu keputusan politik, maka independensi yudisial itu runtuh. Hukum seolah menjadi lilin: bisa dibentuk sesuai kehendak pemegang kekuasaan.
2. Kesenjangan Hukum (Two-Tier Justice System)
Dampak paling berbahaya adalah munculnya persepsi di masyarakat tentang adanya “dua hukum” di Indonesia. Hukum pertama berlaku untuk rakyat biasa: mencuri ringan, bersalah karena ketidaktahuan, atau kasus perdata kecil akan ditindak tegas tanpa kompromi. Hukum kedua berlaku untuk elite politik dan pejabat: vonis hukuman yang berat dapat dinegosiasikan melalui pintu belakang kekuasaan pengampunan.
Hal ini secara langsung menghancurkan rasa keadilan dan menumbuhkan sinisme publik terhadap institusi penegak hukum. Legitmasi hukum pun hilang, digantikan oleh apatis sosial.
3. Moral Hazard dan Hilangnya Efek Jera
Ketika para pelaku kejahatan (terutama koruptor) melihat bahwa pintu pengampunan terbuka lebar, efek jera dari hukuman pidana akan hilang. Mereka akan menilai bahwa hukuman hanyalah “biaya” sementara yang bisa dihapus atau diringankan asalkan memiliki akses atau koneksi politik yang kuat. Hal ini akan memicu moral hazard sistemik.
Mendisiplinkan Kekuasaan Pengampunan
Instrumen pardoning powers ini memang tidak bisa dihapus, tetapi penggunaannya harus didisiplinkan secara ketat dan diaudit secara terbuka.
-
Transparansi Mutlak: Publik dan civil society harus mendesak agar setiap keputusan Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi harus disertai dengan alasan faktual dan hukum yang transparan, bukan sekadar pertimbangan politik. Dasar koreksi hukum atau kekeliruan fakta yang mendasari harus dibuka, mengingat instrumen ini tidak melalui proses pengadilan ulang.
-
Pembatasan Subjek: Penggunaan rehabilitasi seharusnya dibatasi secara ketat pada kasus-kasus miscarriage of justice (kesalahan peradilan murni) dan tidak boleh digunakan untuk membatalkan vonis inkracht pada kasus-kasus yang merugikan keuangan negara (korupsi) atau pelanggaran HAM berat.
-
Memperkuat Peran MA: Pertimbangan Mahkamah Agung untuk Grasi/Rehabilitasi dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk Amnesti/Abolisi harus menjadi filter substantif yang kuat, bukan sekadar stempel legitimasi politik.
Hak Prerogatif Presiden untuk pengampunan adalah pedang bermata dua: ia bisa menjadi alat mulia untuk menegakkan keadilan yang terabaikan, tetapi juga bisa menjadi senjata politik yang melemahkan sistem.
Jika instrumen ini terus digunakan untuk menyelamatkan elite, melindungi koruptor, atau memuluskan kepentingan politik sesaat, maka kita sedang menuju pada sistem hukum yang kehilangan martabatnya. Masa depan sistem hukum yang sehat tergantung pada komitmen kita bersama—terutama Presiden, MA, dan DPR—untuk memastikan bahwa kekuasaan pengampunan digunakan demi keadilan sejati, bukan demi politik kekuasaan.
Oleh: Ketua YLBH Samin Sami Aji (Ch Harno)